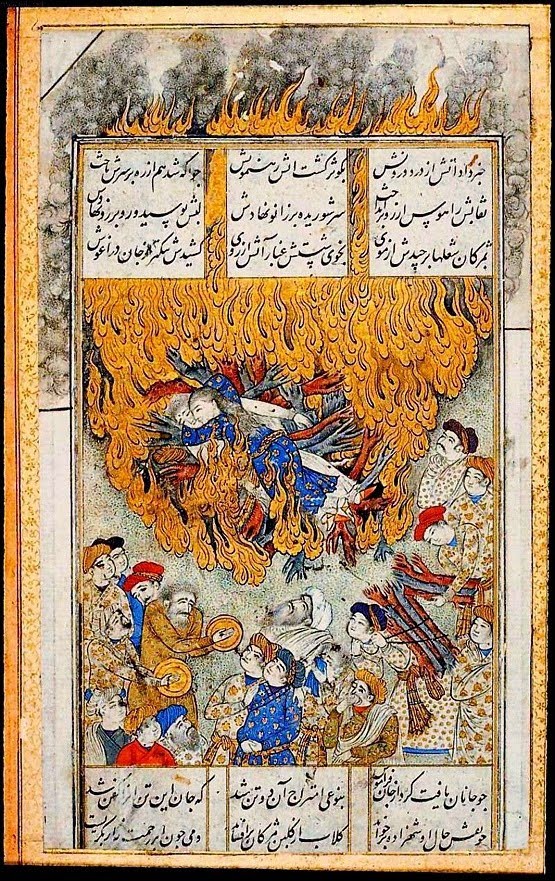09.07.2007.
Cerita saya berawal dari empat tahun yang lalu, sewaktu membaca tulisan Dr.JJ. Kusni dalam buku “Masalah Etnis dan pembangunan”. Dalam salah satu tulisannya, beliau membahas sebuah novel yang berjudul “Lonceng Kematian” karya Ray Rizal, cerita tentang kehidupan orang Dayak Punan di Kalimantan Timur. Dalam pembahasannya, beberapa tulisan beliau (J.J Kusni) “mengetuk” kepala saya dengan keras, dimana dengan ciri khasnya yang tajam ia menulis,
“Ketika Kalimantan sudah mulai diusahakan seperti sekarang, orang-orang Dayak makin terdesak dan terdesak saja. Siapa yang memperdulikan mereka? Mengapa bertanya kepada orang luar dan tidak mengalamatkan pertanyaan kepada yang paling bersangkutan langsung yaitu etnik itu sendiri? Pernahkah kemajuan dan pembangunan berkembang merata karena belas kasihan?”.
Mak deg! Kata-kata “belas kasihan” itu mendengung di kepala saya. Sering sekali saya dengar (langsung di depan telinga saya) komentar dari orang-orang asing tentang Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung intinya adalah “mengasihani” Indonesia. “poor Indonesia, poor country, poor people” dan lain sebagainya, saya yang mendengar ikut mantuk-mantuk seperti burung Tekukur, iya ya, kasihan bangsaku. Sebagai seorang peneliti, sering saya berjumpa dengan peneliti asing yang mempunyai “cita-cita” untuk memperkenalkan Indonesia lebih jauh, menulis tentang Indonesia, tentang budayanya, tentang sejarahnya, pokoke semuanya yang berbau Indonesia, dan saya yang peneliti lokal, mantuk-mantuk lagi, terkagum-kagum mendengar betapa tinggi cita-citanya bagi bangsa saya. Tetapi, lagi-lagi tulisan J.J. Kusni, mengetuk kepala saya yang mantuk-mantuk, tulisnya
“Apakah yang bisa diharapkan dari peneliti asing seperti Nanette (tokoh dalam novel “Lonceng Kematian”), misalnya. Seusai penelitian dan mengumpulkan data, iapun kembali ke Prancis, dan orang Dayak yang ditelitinya berada di hutan Kaltim, sementara Nanette dengan bahan-bahannya tentang Dayak boleh jadi kian memperkokoh posisi di Lembaga Pusat Penelitian Ilmiah Prancis. [...] Lalu untuk manusia, untuk orang Punan, kaum pengembara yang selama ini hidup di hutan dan ingin dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat, siapakah yang perduli?” [...] Adakah tanggapan positif dari masyarakat dan lembaga terkait untuk segera melakukan tindakan penyelamatan? [..] Tapi sungguh mustahil apabila orang-orang Dayak sendiri menjadi manusia tidak perduli atas nasib diri sendiri. Jika memang demikian, janganlah menangisi langit dan bumi melihat kepunahan diri dari permukaan bumi, dan apabila benar-benar demikian maka betul lonceng kematian alias bamba (gong kematian) sudah ditabuh [..]. Dayak hanyalah suatu kasus, karena nama ini bisa saja digantikan dengan nama etnik-etnik lainnya.Apakah saya pesimis? Boleh jadi ya, tapi boleh jadi tidak, karena yang nampaknya pesimis bisa berganti kualitas menjadi sesuatu positif apabila ia membangkitkan kesadaran dan mendorong tindakan menjawab mengalahkan tantangan. Mudah-mudahan!”
Aduh! Saya seperti digodam dengan palu besar, sebagai peneliti kok aksi saya selama ini yah mantuk-mantuk saja, “NATO” kebanyakkan bla, bla, bla, mengalihkan pembicaraan dengan alasan belum ada sponsor, belum top jadi tidak ada yang mau membiayai, mau riset ke pedalaman saja masih menghitung dana yang baru sebatas jumlah “jemari tangan kanan”, belum termasuk “jemari tangan kiri”, lha tidak bisa tepuk tangan toh? Pokoke banyak alasan saya untuk tidak “beraksi”yang akhirnya saya jadi mati kutu digodam tulisan J.J. Kusni. Mengadulah saya ke suami tersayang, berbagi rasa malu, kan dia juga peneliti, walaupun bukan peneliti lokal, mengadu juga ke orang tua dan mertua sekaligus mencari jalan keluar, yang hasilnya lumayan untuk menggenapi dana riset beberapa bulan ke pedalaman.
Hasil riset beberapa bulan hanya berbentuk artikel sebanyak beberapa lembar yang disodorkan ke kanan dan kiri tetapi ditolak oleh berbagai lembaga penerbit. Kenapa? Kurang populer nama penelitinya, masih bau kencur, kurang komersil, tidak ada dukungan nama institusi besar, alasan klasik yang juga berlaku di dunia penelitian. Tapi maju terus pantang mundur, lebih baik bolak-balik cari penerbit dari pada “digodam” dengan rasa malu. Sampai akhirnya artikel kami berdua diterima dengan tangan lebar oleh sebuah badan penelitian di Amerika, wah senangnya bisa berhasil. Tapi tunggu dulu, mana hasil konkritnya? Bah! Ternyata kurang berdampak besar untuk sebuah peradaban, hanya setitik debu di lautan pasir! Kami berdua mulai memasuki tahap berikutnya, mencoba lembaga pemerintah, sebuah Museum Budaya di kota Lugano, tepatnya terletak di bagian selatan Swiss, hanya beberapa kilometer dari perbatasan Swiss-Itali.
Pertama kali saya mengunjungi museum tersebut, saya terpukau dengan banyaknya benda-benda dari Indonesia, mengalahkan koleksi museum Musée de l'Homme di Paris yang dipamerkan untuk umum (sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar koleksi dari Indonesia “terkubur” di gudang Musée de l'Homme, sedih lagi ya?). Setelah habis rasa kagumnya, datanglah rasa sedih, ya sedih benar nasib Indonesia, koleksi dari pulau Borneo semuanya ditulis Malaysia, tidak ada secuilpun bertuliskan INDONESIA. Bahkan salah satu nama suku dayak yang jelas-jelasan berada di Indonesia, nama negara asal bertuliskan juga Malaysia. Bosan saya menangis dan mengeluh! Bosan “dijajah” terus oleh bangsa lain. Saatnya untuk bertindak, walaupun kecewa dengan pemerintah yang sebagian amburadul tetapi sebuah peradaban adalah akar dari sebuah bangsa. Walaupun saya sangat dikecewakan oleh hukum di Indonesia, tetapi peradaban bangsa Indonesia adalah pohon yang membesarkan saya, intinya, saya bosan mendengar dan membaca definisi Borneo = Malaysia (Brunei saja dicuekin), padahal nama Borneo “tercipta” pada tahun 1521 karena “kesalahpahaman” dari Antonio Pigafetta seorang jurnalis Italia yang ikut dalam pelayaran ekspedisi Ferdinand Magellan.
Pigafetta salah kaprah dalam menulis laporan perjalanan, dimana saat ia berlabuh di sebuah pelabuhan, ia terpukau dengan sambutan yang sangat istimewa, menaiki gajah yang berbajukan emas (emasnya pasti buanyakk), melihat rumah-rumah besar (rumah betang) yang bisa memuat 50 orang Eropa. Saat ia menanyakan nama tempat tersebut maka penduduk lokal pun menjawab bahwa ia saat itu berada di Bornei (sekarang bernama Brunei Darussalam ). Pulanglah Pigafetta dengan laporan bahwa ia telah berlabuh di sebuah pulau yang sangat besar dan kaya raya yang bernama Bornei dan akhirnya karena mengikuti lidah orang eropa maka nama “Bornei” menjadi “Borneo”. Gemblung ya, memang susah-susah gampang menjadi jurnalis.Padahal orang melayu (malaysian) yang menetap di pulau tersebut saat itu (tahun 1500) sudah mengenal dan mengetahui nama pulau dengan nama “Kalamantan”.
Karena bosan mendengar omelan saya sendiri, begitu juga suami saya sampai “penuh” telinganya mendengar keluhan saya, maka kami memberanikan diri untuk menulis ke Museum Budaya Lugano, menawarkan diri untuk “mengoreksi” secara sukarela, tidak digajipun ya tidak apa-apa karena bagi kami sebuah kebenaran adalah suatu bayaran yang mahal. Tapi tunggu punya tunggu, gigit jari saja yang terjadi, penolakkan dari pihak museumpun tidak terdengar, mungkin tawaran kami dianggap “aneh bin ajaib”. Ya sudah, daripada marah-marah ya berdoa saja menunggu waktu untuk mengungkapkan kebenaran, sambil “cuap-cuap” di sekitar tempat tinggal berbagi pengetahuan tentang Indonesia.
Pada tahun 2005, kami mendengar pergantian pengurus di Museum Budaya Lugano dimana pemimpin yang baru adalah seorang profesor asal Itali ahli budaya akan Sepik dan Bali. Ya dicoba lagi menawarkan diri kembali ke Museum Budaya Lugano, tidak ada salahnya sudah kebal dengan penolakan, jadi kami maju lagi “bertempur” di susunan pengurus yang baru.
“Bak gayung bersambut” jadilah kami “memandikan” Indonesia yang “kotor ketutupan debu ketidakbenaran”. Pemimpin museum yang baru setuju untuk memberikan “gayung” kepada kami dalam mengoreksi beberapa koleksi benda-benda budaya di Museum Budaya Lugano, bahkan bukan hanya “gayung” yang diberikan kepada kami berdua, tetapi juga “tempayan besar penuh berisi air” untuk membersihkan. Kami berdua dipercayakan dalam mengorganisir Pameran Budaya akan benda-benda budaya dari pulau yang pernah dikenal dengan nama Pulau Bagawan Bawi Lewu Telo (Riwut, 2003 :3),Burnéi (Stanley, 1874:108), Nusa Tanjung Negara dan Pulo Kalamantan (Saint John, 1847:15). Wah lompat-lompat ditempat kami, senangnya bukan kepalang serta takutnya hampir menjadi penghalang. Senang karena waktu yang ditunggu-tunggu sudah di depan mata, takut karena yang akan digelar adalah martabat bangsa.
Wara-wiri mengatur acara pameran ternyata lebih pusing daripada membuat makalah ilmiah, makanya karena sudah kadung pusing ya sekalian saya coba-coba membikin acara “seramai” mungkin. Dari sebanyak 39 objek budaya dari pulau Borneo yang dipamerkan, hanya 5 objek yang positif dari Malaysia, oleh karena itu, bisa dikatakan yang mejadi “tuan rumah” dari pameran adalah INDONESIA. Jadi saya mengusulkan agar setidaknya pemerintah Indonesia bisa membuka acara pameran tersebut.
Dikarenakan sebagian besar objek berasal dari Indonesia, oleh karena itu pihak kota Lugano setuju untuk mengundang Duta Besar Republik Indonesia, Ibu Lucia Helwinda Rustam dan juga mengundang langsung Gubernur Kalimantan Tengah serta menanggung seluruh biaya transportasi dari Indonesia hingga tiba di Lugano, akomodasi selama di Lugano serta kunjungan-kunjungan sosial ke berbagai tempat di Lugano, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan akan kebesaran peradaban Kalimantan di Indonesia. Saya (kembali) mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengusulkan (lagi) ke kota Lugano untuk mengadakan seminar tentang Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi tapi tampaknya, “gayung belum tersambut”, karena saat ini negara yang menjadi prioritas bagi jaringan bisnis Switzerland (OSEC) adalah negara Thailand, alasan ketidakstabilan politik menjadi landasan untuk mendudukkan Indonesia di “lantai”, ya gedebuk lagi saya ndeprok “menunggu” lagi.
Singkatnya, pameran tersebut berhasil dilaksanakan dibantu oleh para “sesepuh” antropolog Kalimantan yang diantaranya adalah Mina (cat: bibi) Nila Riwut, bapak Antonio Guerreiro dan bapak Bernard Sellato dari Perancis, dimana beliau mampu bercakap dalam bahasa daerah, lebih canggih dari saya sendiri (malu jeg!). Pameran yang berjudul “PATONG. Great Figures Carved by the People of Borneo” bertempat di Galleria Gottardo, Lugano dan berlangsung selama tiga bulan dari tanggal 23 Mai hingga 25 Agustus 2007, bisa lihat di website http://www.galleria-gottardo.org/galleria_gottardo/en/Index.html.Saat pembukaan pameran, tanggal 23 Mai 2007, Duta Besar Indonesia, Ibu Lucia H Rustam memberikan kata sambutan yang sangat menyentuh hati saya. Baru sekali saya bertemu dengan para pejabat pemerintah yang sangat “membumi” dimana kedua kakinya “menginjak tanah” dengan pasti. Pujian, rasa kagum dan hormat saya kepada beliau. Begitu juga dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan istri, Bapak Teras Narang dan Ibu Moenartining, mereka berdua mengangkat wajah dengan tegak, bangga memperkenalkan Kalimantan kepada masyarakat Internasional, rasa percaya diri dan pengetahuan mereka yang luas membuat Indonesia terlihat besar di kerumunan orang-orang berkulit putih. Jauh sekali dengan pejabat-pejabat pemerintah lainnya yang pernah saya temui (terutama pada pembukaan pameran budaya di Eropa), setidaknya mereka bagaikan angin segar di tengah-tengah polusi pemerintahan.
Pameran berlangsung dengan sukses, pengunjung berdatangan dari berbagai negara. Dan yang menarik dalam pameran adalah program “guided visit ” untuk grup dari perusahaan, lembaga maupun instansi perbankan, dimana kunjungan juga dilengkapi dengan pengetahuan akan budaya dan sejarah. Nah yang ini menjadi bagian kami berdua, terutama saya yang paling “cerewet” mengenalkan Indonesia kepada para usahawan.Grup pertama yang berpartisipasi dalam program tersebut adalah sebuah grup bank besar Swiss yang beranggotakan 40 orang. Kami berdua agak grogi di depan para bankir, bagaimana caranya berbicara antropologi dengan para bankir yang berkutat dengan angka? Akhirnya suasana yang kaku mencair dengan cepat, apalagi saat mereka mengajukan pertanyaan, sampai terkaget-kaget saya dengan pertanyaan para bankir.
“Adakah gorila di Indonesia? Indonesia tidak sama dengan Malaysia? Adakah lapangan terbang? Bisakah menggunakan dolar? Apakah peradaban suku Dayak masih eksis di Indonesia?”
Saat menjawab pertanyaan mereka, kembali terngiang – ngiang di telinga saya, pesan Ibu Moenartining dan Bapak Teras Narang sebelum memasuki pintu masuk imigrasi bandara Lugano untuk pulang ke Indonesia,
Cerita saya berawal dari empat tahun yang lalu, sewaktu membaca tulisan Dr.JJ. Kusni dalam buku “Masalah Etnis dan pembangunan”. Dalam salah satu tulisannya, beliau membahas sebuah novel yang berjudul “Lonceng Kematian” karya Ray Rizal, cerita tentang kehidupan orang Dayak Punan di Kalimantan Timur. Dalam pembahasannya, beberapa tulisan beliau (J.J Kusni) “mengetuk” kepala saya dengan keras, dimana dengan ciri khasnya yang tajam ia menulis,
“Ketika Kalimantan sudah mulai diusahakan seperti sekarang, orang-orang Dayak makin terdesak dan terdesak saja. Siapa yang memperdulikan mereka? Mengapa bertanya kepada orang luar dan tidak mengalamatkan pertanyaan kepada yang paling bersangkutan langsung yaitu etnik itu sendiri? Pernahkah kemajuan dan pembangunan berkembang merata karena belas kasihan?”.
Mak deg! Kata-kata “belas kasihan” itu mendengung di kepala saya. Sering sekali saya dengar (langsung di depan telinga saya) komentar dari orang-orang asing tentang Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung intinya adalah “mengasihani” Indonesia. “poor Indonesia, poor country, poor people” dan lain sebagainya, saya yang mendengar ikut mantuk-mantuk seperti burung Tekukur, iya ya, kasihan bangsaku. Sebagai seorang peneliti, sering saya berjumpa dengan peneliti asing yang mempunyai “cita-cita” untuk memperkenalkan Indonesia lebih jauh, menulis tentang Indonesia, tentang budayanya, tentang sejarahnya, pokoke semuanya yang berbau Indonesia, dan saya yang peneliti lokal, mantuk-mantuk lagi, terkagum-kagum mendengar betapa tinggi cita-citanya bagi bangsa saya. Tetapi, lagi-lagi tulisan J.J. Kusni, mengetuk kepala saya yang mantuk-mantuk, tulisnya
“Apakah yang bisa diharapkan dari peneliti asing seperti Nanette (tokoh dalam novel “Lonceng Kematian”), misalnya. Seusai penelitian dan mengumpulkan data, iapun kembali ke Prancis, dan orang Dayak yang ditelitinya berada di hutan Kaltim, sementara Nanette dengan bahan-bahannya tentang Dayak boleh jadi kian memperkokoh posisi di Lembaga Pusat Penelitian Ilmiah Prancis. [...] Lalu untuk manusia, untuk orang Punan, kaum pengembara yang selama ini hidup di hutan dan ingin dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat, siapakah yang perduli?” [...] Adakah tanggapan positif dari masyarakat dan lembaga terkait untuk segera melakukan tindakan penyelamatan? [..] Tapi sungguh mustahil apabila orang-orang Dayak sendiri menjadi manusia tidak perduli atas nasib diri sendiri. Jika memang demikian, janganlah menangisi langit dan bumi melihat kepunahan diri dari permukaan bumi, dan apabila benar-benar demikian maka betul lonceng kematian alias bamba (gong kematian) sudah ditabuh [..]. Dayak hanyalah suatu kasus, karena nama ini bisa saja digantikan dengan nama etnik-etnik lainnya.Apakah saya pesimis? Boleh jadi ya, tapi boleh jadi tidak, karena yang nampaknya pesimis bisa berganti kualitas menjadi sesuatu positif apabila ia membangkitkan kesadaran dan mendorong tindakan menjawab mengalahkan tantangan. Mudah-mudahan!”
Aduh! Saya seperti digodam dengan palu besar, sebagai peneliti kok aksi saya selama ini yah mantuk-mantuk saja, “NATO” kebanyakkan bla, bla, bla, mengalihkan pembicaraan dengan alasan belum ada sponsor, belum top jadi tidak ada yang mau membiayai, mau riset ke pedalaman saja masih menghitung dana yang baru sebatas jumlah “jemari tangan kanan”, belum termasuk “jemari tangan kiri”, lha tidak bisa tepuk tangan toh? Pokoke banyak alasan saya untuk tidak “beraksi”yang akhirnya saya jadi mati kutu digodam tulisan J.J. Kusni. Mengadulah saya ke suami tersayang, berbagi rasa malu, kan dia juga peneliti, walaupun bukan peneliti lokal, mengadu juga ke orang tua dan mertua sekaligus mencari jalan keluar, yang hasilnya lumayan untuk menggenapi dana riset beberapa bulan ke pedalaman.
Hasil riset beberapa bulan hanya berbentuk artikel sebanyak beberapa lembar yang disodorkan ke kanan dan kiri tetapi ditolak oleh berbagai lembaga penerbit. Kenapa? Kurang populer nama penelitinya, masih bau kencur, kurang komersil, tidak ada dukungan nama institusi besar, alasan klasik yang juga berlaku di dunia penelitian. Tapi maju terus pantang mundur, lebih baik bolak-balik cari penerbit dari pada “digodam” dengan rasa malu. Sampai akhirnya artikel kami berdua diterima dengan tangan lebar oleh sebuah badan penelitian di Amerika, wah senangnya bisa berhasil. Tapi tunggu dulu, mana hasil konkritnya? Bah! Ternyata kurang berdampak besar untuk sebuah peradaban, hanya setitik debu di lautan pasir! Kami berdua mulai memasuki tahap berikutnya, mencoba lembaga pemerintah, sebuah Museum Budaya di kota Lugano, tepatnya terletak di bagian selatan Swiss, hanya beberapa kilometer dari perbatasan Swiss-Itali.
Pertama kali saya mengunjungi museum tersebut, saya terpukau dengan banyaknya benda-benda dari Indonesia, mengalahkan koleksi museum Musée de l'Homme di Paris yang dipamerkan untuk umum (sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar koleksi dari Indonesia “terkubur” di gudang Musée de l'Homme, sedih lagi ya?). Setelah habis rasa kagumnya, datanglah rasa sedih, ya sedih benar nasib Indonesia, koleksi dari pulau Borneo semuanya ditulis Malaysia, tidak ada secuilpun bertuliskan INDONESIA. Bahkan salah satu nama suku dayak yang jelas-jelasan berada di Indonesia, nama negara asal bertuliskan juga Malaysia. Bosan saya menangis dan mengeluh! Bosan “dijajah” terus oleh bangsa lain. Saatnya untuk bertindak, walaupun kecewa dengan pemerintah yang sebagian amburadul tetapi sebuah peradaban adalah akar dari sebuah bangsa. Walaupun saya sangat dikecewakan oleh hukum di Indonesia, tetapi peradaban bangsa Indonesia adalah pohon yang membesarkan saya, intinya, saya bosan mendengar dan membaca definisi Borneo = Malaysia (Brunei saja dicuekin), padahal nama Borneo “tercipta” pada tahun 1521 karena “kesalahpahaman” dari Antonio Pigafetta seorang jurnalis Italia yang ikut dalam pelayaran ekspedisi Ferdinand Magellan.
Pigafetta salah kaprah dalam menulis laporan perjalanan, dimana saat ia berlabuh di sebuah pelabuhan, ia terpukau dengan sambutan yang sangat istimewa, menaiki gajah yang berbajukan emas (emasnya pasti buanyakk), melihat rumah-rumah besar (rumah betang) yang bisa memuat 50 orang Eropa. Saat ia menanyakan nama tempat tersebut maka penduduk lokal pun menjawab bahwa ia saat itu berada di Bornei (sekarang bernama Brunei Darussalam ). Pulanglah Pigafetta dengan laporan bahwa ia telah berlabuh di sebuah pulau yang sangat besar dan kaya raya yang bernama Bornei dan akhirnya karena mengikuti lidah orang eropa maka nama “Bornei” menjadi “Borneo”. Gemblung ya, memang susah-susah gampang menjadi jurnalis.Padahal orang melayu (malaysian) yang menetap di pulau tersebut saat itu (tahun 1500) sudah mengenal dan mengetahui nama pulau dengan nama “Kalamantan”.
Karena bosan mendengar omelan saya sendiri, begitu juga suami saya sampai “penuh” telinganya mendengar keluhan saya, maka kami memberanikan diri untuk menulis ke Museum Budaya Lugano, menawarkan diri untuk “mengoreksi” secara sukarela, tidak digajipun ya tidak apa-apa karena bagi kami sebuah kebenaran adalah suatu bayaran yang mahal. Tapi tunggu punya tunggu, gigit jari saja yang terjadi, penolakkan dari pihak museumpun tidak terdengar, mungkin tawaran kami dianggap “aneh bin ajaib”. Ya sudah, daripada marah-marah ya berdoa saja menunggu waktu untuk mengungkapkan kebenaran, sambil “cuap-cuap” di sekitar tempat tinggal berbagi pengetahuan tentang Indonesia.
Pada tahun 2005, kami mendengar pergantian pengurus di Museum Budaya Lugano dimana pemimpin yang baru adalah seorang profesor asal Itali ahli budaya akan Sepik dan Bali. Ya dicoba lagi menawarkan diri kembali ke Museum Budaya Lugano, tidak ada salahnya sudah kebal dengan penolakan, jadi kami maju lagi “bertempur” di susunan pengurus yang baru.
“Bak gayung bersambut” jadilah kami “memandikan” Indonesia yang “kotor ketutupan debu ketidakbenaran”. Pemimpin museum yang baru setuju untuk memberikan “gayung” kepada kami dalam mengoreksi beberapa koleksi benda-benda budaya di Museum Budaya Lugano, bahkan bukan hanya “gayung” yang diberikan kepada kami berdua, tetapi juga “tempayan besar penuh berisi air” untuk membersihkan. Kami berdua dipercayakan dalam mengorganisir Pameran Budaya akan benda-benda budaya dari pulau yang pernah dikenal dengan nama Pulau Bagawan Bawi Lewu Telo (Riwut, 2003 :3),Burnéi (Stanley, 1874:108), Nusa Tanjung Negara dan Pulo Kalamantan (Saint John, 1847:15). Wah lompat-lompat ditempat kami, senangnya bukan kepalang serta takutnya hampir menjadi penghalang. Senang karena waktu yang ditunggu-tunggu sudah di depan mata, takut karena yang akan digelar adalah martabat bangsa.
Wara-wiri mengatur acara pameran ternyata lebih pusing daripada membuat makalah ilmiah, makanya karena sudah kadung pusing ya sekalian saya coba-coba membikin acara “seramai” mungkin. Dari sebanyak 39 objek budaya dari pulau Borneo yang dipamerkan, hanya 5 objek yang positif dari Malaysia, oleh karena itu, bisa dikatakan yang mejadi “tuan rumah” dari pameran adalah INDONESIA. Jadi saya mengusulkan agar setidaknya pemerintah Indonesia bisa membuka acara pameran tersebut.
Dikarenakan sebagian besar objek berasal dari Indonesia, oleh karena itu pihak kota Lugano setuju untuk mengundang Duta Besar Republik Indonesia, Ibu Lucia Helwinda Rustam dan juga mengundang langsung Gubernur Kalimantan Tengah serta menanggung seluruh biaya transportasi dari Indonesia hingga tiba di Lugano, akomodasi selama di Lugano serta kunjungan-kunjungan sosial ke berbagai tempat di Lugano, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan akan kebesaran peradaban Kalimantan di Indonesia. Saya (kembali) mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengusulkan (lagi) ke kota Lugano untuk mengadakan seminar tentang Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi tapi tampaknya, “gayung belum tersambut”, karena saat ini negara yang menjadi prioritas bagi jaringan bisnis Switzerland (OSEC) adalah negara Thailand, alasan ketidakstabilan politik menjadi landasan untuk mendudukkan Indonesia di “lantai”, ya gedebuk lagi saya ndeprok “menunggu” lagi.
Singkatnya, pameran tersebut berhasil dilaksanakan dibantu oleh para “sesepuh” antropolog Kalimantan yang diantaranya adalah Mina (cat: bibi) Nila Riwut, bapak Antonio Guerreiro dan bapak Bernard Sellato dari Perancis, dimana beliau mampu bercakap dalam bahasa daerah, lebih canggih dari saya sendiri (malu jeg!). Pameran yang berjudul “PATONG. Great Figures Carved by the People of Borneo” bertempat di Galleria Gottardo, Lugano dan berlangsung selama tiga bulan dari tanggal 23 Mai hingga 25 Agustus 2007, bisa lihat di website http://www.galleria-gottardo.org/galleria_gottardo/en/Index.html.Saat pembukaan pameran, tanggal 23 Mai 2007, Duta Besar Indonesia, Ibu Lucia H Rustam memberikan kata sambutan yang sangat menyentuh hati saya. Baru sekali saya bertemu dengan para pejabat pemerintah yang sangat “membumi” dimana kedua kakinya “menginjak tanah” dengan pasti. Pujian, rasa kagum dan hormat saya kepada beliau. Begitu juga dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan istri, Bapak Teras Narang dan Ibu Moenartining, mereka berdua mengangkat wajah dengan tegak, bangga memperkenalkan Kalimantan kepada masyarakat Internasional, rasa percaya diri dan pengetahuan mereka yang luas membuat Indonesia terlihat besar di kerumunan orang-orang berkulit putih. Jauh sekali dengan pejabat-pejabat pemerintah lainnya yang pernah saya temui (terutama pada pembukaan pameran budaya di Eropa), setidaknya mereka bagaikan angin segar di tengah-tengah polusi pemerintahan.
Pameran berlangsung dengan sukses, pengunjung berdatangan dari berbagai negara. Dan yang menarik dalam pameran adalah program “guided visit ” untuk grup dari perusahaan, lembaga maupun instansi perbankan, dimana kunjungan juga dilengkapi dengan pengetahuan akan budaya dan sejarah. Nah yang ini menjadi bagian kami berdua, terutama saya yang paling “cerewet” mengenalkan Indonesia kepada para usahawan.Grup pertama yang berpartisipasi dalam program tersebut adalah sebuah grup bank besar Swiss yang beranggotakan 40 orang. Kami berdua agak grogi di depan para bankir, bagaimana caranya berbicara antropologi dengan para bankir yang berkutat dengan angka? Akhirnya suasana yang kaku mencair dengan cepat, apalagi saat mereka mengajukan pertanyaan, sampai terkaget-kaget saya dengan pertanyaan para bankir.
“Adakah gorila di Indonesia? Indonesia tidak sama dengan Malaysia? Adakah lapangan terbang? Bisakah menggunakan dolar? Apakah peradaban suku Dayak masih eksis di Indonesia?”
Saat menjawab pertanyaan mereka, kembali terngiang – ngiang di telinga saya, pesan Ibu Moenartining dan Bapak Teras Narang sebelum memasuki pintu masuk imigrasi bandara Lugano untuk pulang ke Indonesia,
“Titip Indonesia ya nak ...”Arita-CH